Mencari Jejak Tuhan dalam Sejarah
| Masa Depan Tuhan |
| Friday, 24 June 2011 | |
| Judul di atas adalah judul buku baru karangan Karen Armstrong, Masa Depan Tuhan (2011) dalam edisi bahasa Indonesia. Aslinya The Case for God: What Religion Really Means. Armstrong adalah penulis keagamaan yang serius, tradisi risetnya kuat, sehingga pantas jika lebih dari 15 bukunya masuk ranking terlaris di dunia. Tuhan dalam kajian Armstrong adalah Tuhan yang menyejarah, yang hidup di tengah dan bersama pemeluknya,Tuhan yang kemudian melahirkan komunitas orang beriman dan sekian banyak tradisi dan institusi agama. Jadi, Tuhan sebagai Yang Mahatinggi dan Absolut tentu tidak dibatasi waktu, tak mengenal kemarin, sekarang, dan masa depan. Bahkan juga tidak terpahami oleh akal pikiran. Kita terlalu banyak berbicara tentang Tuhan akhir-akhir ini dan apa yang kita katakan sering dangkal, kata Armstrong (hlm 9). Di samping menyajikan dinamika jejak-jejak Tuhan dan pengaruhnya dalam sejarah manusia, buku ini secara tidak langsung menjawab paham ateisme modern yang berciri sangat rasional dan ilmiah (scientific atheism) yang telah memukau masyarakat modern dan anak-anak muda di Barat. Selama abad ke-16 dan ke-17, di Barat lahir peradaban baru yang diatur dengan rasionalitas ilmiah dan ekonomi yang berbasis pada teknologi serta penanaman modal. Sejak itu satu-satunya ukuran kebenaran adalah metode ilmiah. Logos mengalahkan mitos. Padahal di dalam mitos keagamaan terkandung kebenaran dan kebajikan yang tidak dapat dijangkau oleh logos. Tafsiran yang serba rasional atas agama menimbulkan dua fenomena baru yang sangat khas: fundamentalisme dan ateisme (hlm 19). Selama ini tokoh yang mengembangkan paham ateisme selalu merujuk pada Feurbach, Karl Marx, Nietzsche, atau Freud yang muncul di abad ke-19. Tetapi sekarang bermunculan paham ateisme baru yang dimotori terutama oleh Richard Dawkins, Christopher Hitchens, dan Sam Harris. Dalam karya-karya mereka akan ditemukan argumentasi ilmiah kontemporer untuk menyerang umat beragama yang masih mempercayai Tuhan dan campur tangan-Nya dalam sejarah.Terhadap serangan dimaksud, buku Armstrong ini turut berdiri sebagai pembelaan terhadap eksistensi agama-agama. Logika dan pendekatan ilmiah, terlebih yang mengandalkan paham empirisisme-positivisme, tidak akan pernah mampu memotret dan menganalisis misteri kehidupan, keberagamaan, dan kebertuhanan. Berbagai karya Armstrong secara serius berhasil menyajikan betapa agama dan keyakinan pada Tuhan selalu hadir pada panggung sejarah dan turut memengaruhi manusia memaknai hidupnya. Agama, keyakinan, dan pemahaman terhadap Tuhan, senantiasa berinteraksi dengan perkembangan sejarah sebuah masyarakat dengan segala aspeknya. Karena itu, katanya, memahami kitab suci hanya sebatas kata-kata literernya akan menyesatkan dan mengalami reduksi, tidak sampai pada pesan inti agama. Di sisi lain, arogansi ilmiah dalam memahami agama telah mendorong munculnya respons balik berupa fundamentalisme agama. Perubahan mindset pemahaman agama dan kehidupan di Eropa sangat dipengaruhi oleh ekspedisi Christopher Columbus pada 1492 yang berhasil menemukan benua baru Amerika, yang disponsori Raja Katolik Ferdinand dan Isabella. Berita keberhasilan ini menyebar bagaikan wabah baru, bahwa di luar Eropa ternyata ada dunia lain yang sangat menarik untuk dieksplorasi. Jadi, ekspedisi, eksplorasi, perpindahan penduduk, dan penyebaran informasi baru selalu melahirkan sintesa budaya baru, yang diawali dengan masalah dan tantangan baru. Hari ini, apa yang terjadi pada abad ke-15 di Eropa telah merata di seluruh dunia melalui jejaring internet dan dunia maya. Masyarakat terkondisikan untuk berani melampaui batas-batas dunia yang diketahui. Perjumpaan dan benturan berbagai tradisi dan informasi budaya serta agama ini telah membuat sebagian besar umat beragama gamang dan kaget (shocked). Bahwa klaim kebenaran, keilahian, dan surga ternyata juga dimiliki oleh kelompok umat agama lain. Sementara itu, ada juga kelompok yang secara gigih menentang adanya Tuhan dan ingin menghapus agama. Perasaan tidak nyaman dan terancam dalam beragama inilah akar munculnya gerakan fundamentalisme. Mengutip Armstrong, fundamentalisme adalah iman yang sangat reduktif. Dalam kecemasan dan ketakutan mereka, kaum fundamentalis sering mendistorsi tradisi yang mereka coba bela, misalnya dengan sangat selektif baca ayat-ayat kitab suci yang membenarkan kekerasan dan permusuhan terhadap umat yang berbeda keyakinan (hlm 470). Kaum fundamentalis yakin bahwa mereka berjuang atas nama Tuhan, tetapi sebenarnya religiositas jenis ini mewakili kemunduran dari Tuhan (hlm 471). Demikianlah, dunia terus berputar. Sejarah terus bergulir merekam sepak terjang pemikiran dan perilaku manusia. Agama pun sering kali jadi sasaran kritik dan caci maki. Tetapi nyatanya agama tetap hidup dan berkembang.Tuhan selalu berada di hati manusia. Ini membenarkan pandangan yang mengatakan bahwa "agama memiliki seribu nyawa". Kalaupun mati satu, masih lebih banyak yang bertahan hidup. Orang boleh saja mengkritik perilaku umat beragama dan berbagai institusi keagamaan yang dibangunnya, tapi kesadaran, kebutuhan dan keyakinan agama masih tetap menggelora. Dengan agama seseorang mencari makna dan tujuan hidup yang lebih hakiki dan mulia. (Prof Dr Komaruddin Hidayat - Rektor UIN Syarif Hidayatullah) |



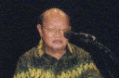 SEJAK saya melihatnya pada tahun 1962 di sekitar Universitas Indonesia, Onghokham selalu tampak dengan baju dan celana khaki yang kusut. Ia selalu membawa satu tas kulit yang mencong; isinya—buku dan lain-lain—selalu berlebihan. Ia terkadang naik sebuah bromfiets yang mencemaskan karena bergoyang-goyang dengan bunyi sember yang seperti menderita.
SEJAK saya melihatnya pada tahun 1962 di sekitar Universitas Indonesia, Onghokham selalu tampak dengan baju dan celana khaki yang kusut. Ia selalu membawa satu tas kulit yang mencong; isinya—buku dan lain-lain—selalu berlebihan. Ia terkadang naik sebuah bromfiets yang mencemaskan karena bergoyang-goyang dengan bunyi sember yang seperti menderita.
